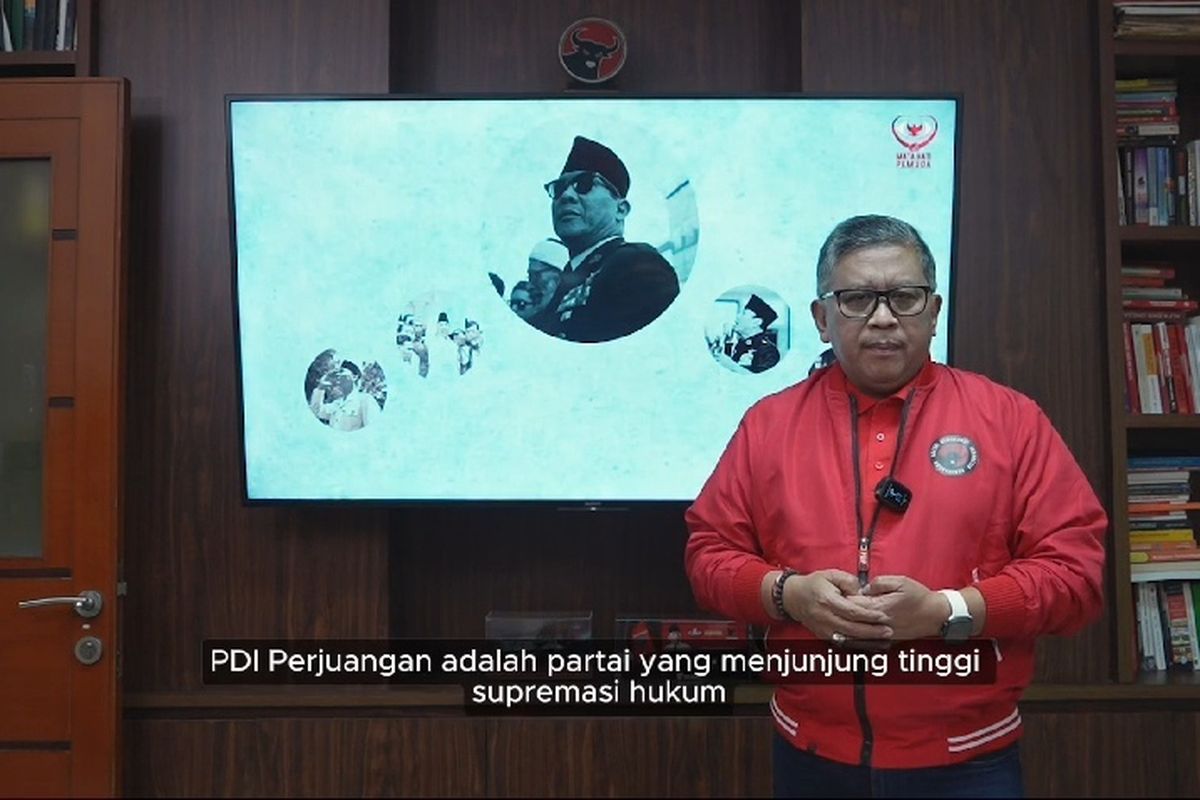Perang Narasi OCCRP Vs Para “Die Hard” Jokowi

DI ERA pemerintahan Jokowi, ada semacam pameo yang berkembang di kalangan tertentu tentang Jokowi dan para pendukungnya.
Kira-kira bunyinya begini. Ada tiga kelompok yang tak bisa atau sangat sulit sekali untuk dinasehati.
Pertama adalah orang yang sedang marah. Kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Dan ketiga adalah pendukung Jokowi.
Boleh jadi banyak pendukung Jokowi yang akhirnya balik badan hanya dalam beberapa tahun pemerintahannya berjalan, termasuk tiga orang yang di akhir tahun lalu, menjadi narasumber utama film dokumentar bertajuk “Dirty Vote”.
Dengan kata lain, tidak semua pendukung Jokowi keras kepala. Namun, esensi dari pameo di atas adalah bahwa barang siapa yang mencoba mengkritik Jokowi, akan berhadapan dengan beberapa tembok. Itulah awal cerita dari pameo tersebut.
Tembok pertama adalah tembok yang seolah-olah merepresentasikan suara rakyat kebanyakan.
Hal itu bisa terjadi karena selama ini Jokowi memang diidentifikasi sebagai perwakilan nonelite yang “climb the ladder” dengan latar “bukan dari lingkaran oligarki politik yang telah menguasai perpolitikan Indonesia sejak era Orde Baru dan Reformasi”.
Jokowi diidentikkan dengan “tetangga kita” alias orang biasa yang diasosiasikan sebagai bagian dari kita. Karena itulah mengapa tagline-nya “Jokowi adalah kita”.
Padahal identifikasi ini secara politik cukup berbahaya sebenarnya. Pasalnya, untuk menjadi seorang pemimpin idealnya dibutuhkan kualifikasi yang tidak mudah dengan rentang perjalanan dan pengalaman yang juga tidak pendek.
Tidak cukup hanya dengan status sosok yang setara dengan tetangga saya atau tetangga Anda.
Jika menyepelekan hal itu, ditakutkan nantinya malah sangat “underqualified”, karena siapa saja bisa menjadi tetangga saya dan Anda, lalu ujung-ujungnya malah merusak negara di akhir kekuasaan pemerintahannya.
Tembok kedua adalah buzzer. Entah Jokowi secara personal atau Jokowi sebagai seorang presiden, diakui atau tidak, memiliki buzzer yang sangat banyak.
Sampai hari ini belum terlalu terungkap siapa dalang ‘beternak’ buzzer sejak 2014 lalu, sehingga sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi, jumlahnya sudah masuk kategori memusingkan kepala di satu sisi dan mendelegitimasi banyak pandangan rasional dan ilmiah para pakar di sisi lain.
Dengan kata lain, pendapat profesor dan pakar pun bisa mentah di hadapan para buzzer, jika itu ternyata bertentangan dengan Jokowi dan pemerintahannya atau bertentangan dengan kepentingan gerbong-gerbong yang ada di belakang Jokowi.
Artinya, OCCRP, yang bagi sebagian besar orang Indonesia bukanlah siapa-siapa, dipastikan akan dirujak sedemikian rupa, karena berani-beraninya untuk menobatkan seorang Jokowi sebagai orang nomor dua terkorup di dunia.
Pada tembok pertama, boleh jadi penobatan OCCRP yang berasal dari voting online dan pendapat para pakar tersebut bisa berkeliaran bak peluru nyasar.
Sebagian masyarakat yang telah “move on” dari Jokowi dan sedang mencoba meraba-raba peluang untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto akan menanggapinya dengan senyuman, tepatnya perpaduan antara senyuman sinis dan getir.
Apalagi jika selama 10 tahun terdahulu mereka adalah pendukung Prabowo Subianto sejati.
Namun, bagi masyarakat yang memang masuk kategori “tetangga Jokowi” tadi, tentu akan muncul rasa marah dan tidak menerima, tapi merasa sudah tidak kontekstual lagi untuk meresponsnya secara agresif layaknya seperti di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Meskipun ada rasa ingin membela dan memaki-maki OCCRP di ruang publik, tapi setelah dipikir-pikir ulang, rasanya “kok” tak ada gunanya juga.
Jokowi toh sudah bukan siapa-siapa lagi, pun di sisi lain rasanya hidup juga “begitu-begitu” saja setelah sepuluh tahun Jokowi berkuasa.
Nah, benturan OCCRP terkeras tentu ada pada tembok kedua, yakni tembok buzzer. Di kandang-kandang buzzer Jokowi, sebagaimana biasanya, dipastikan genderang perang sedang dinyalakan.
Karena di kandang-kandang mereka, apapun bentuk serangan terhadap Jokowi akan “halal” untuk diserang balik dengan segala cara dan segala senjata.
Namun lagi-lagi, sepanjang pengamatan saya di lini media sosial, isu ini tetap tidak “kece”. Hanya sebagian kecil buzzer yang menanggapi dan mengulasnya, itu pun subjektifnya agak kurang “ketulungan”.
Lantas, bagaimana dengan kalangan elite? Sepanjang pengamatan saya, belum ada yang berniat menanggapi isu ini di kalangan elite pemerintahan yang sedang berkuasa.
Sikap tersebut sangat bisa dipahami. Situasinya akan sangat berbeda jika isu ini muncul di saat Jokowi masih berkuasa. Sebagian besar elite yang berada di dalam pemerintahan akan berusaha “mencari muka” untuk mempertahankan reputasi Jokowi.
Eranya sudah bukan Jokowi lagi. Tanggapan elite-elite di dalam pemerintahan saat ini cenderung “nihil”.
Boleh jadi karena tidak terkait lagi dengan urusan pemerintahan atau boleh jadi juga tak mau “ketempelan” oleh isu tersebut alias khawatir diangggap sebagai bagian yang pernah mendukung “pemimpin terkorup”, belum diketahui pasti motivasi “kenihilan” tanggapan elite ini.
Terpantau memang beberapa elite atau tokoh yang pernah berjaya di era sepuluh tahun lalu sebagai pembela Jokowi di ruang publik, mempertanyakan klaim OCCRP tersebut di satu sisi dan berusaha membela Jokowi dengan gaya yang agak hati-hati di sisi lain alias “tidak seugal-ugalan” dulu. Namun gelombangnya tidak besar.
Sepengetahuan saya, tanpa perlu menyebut nama, jumlahnya bisa dihitung jari alias tak sebanyak tokoh yang membela Jokowi di masa pemerintahan Jokowi sendiri.
Sementara itu bagi OCCRP sendiri, pengumuman daftar terkorup dunia ini, khusus untuk konteks Indonesia, agak kurang pas waktunya, sehingga kehadirannya dikaitkan langsung dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.
Daftar tersebut dihadirkan pas di saat “perang” antara Jokowi dan Hasto Kristiyanto sedang berlangsung.
Walhasil, entah benar atau tidak, kelahiran daftar dari OCCRP tersebut dicandra sebagai salah satu senjata yang dipakai oleh salah satu pihak di dalam perang antara kedua tokoh ini.
Lantas, bagaimana kita harus memahami penobatan Jokowi oleh OCCRP ini?
Pertama, apakah Jokowi benar-benar “korup” atau hanya dicitrakan “korup” oleh OCCRP? Kedua, apakah perlu mendelegitimasi OCCRP alias tidak menerima Jokowi dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup?
Ketiga, apakah perlu mengait-ngaitkannya dengan salah satu media nasional yang selama ini memang menjadi bagian dari OCCRP, lalu menyerangnya?
Pertama, menurut saya, karena klaim tersebut berdasarkan survei, maka harus diterima sebagai hasil survei saja.
Selama ini, misalnya, lembaga Transparansi Internasional (TI) selalu merilis indeks persepsi korupsi dan menyebut satu persatu lembaga yang disurvei oleh TI di dalam pengumumannya.
Nampaknya setelah pengumuman tersebut, semuanya “fine-fine” saja. TI sebagai lembaga yang memang memiliki “domain” di sana juga “fine-fine” saja. Tak ada masalah.
Namun, hasil rilis TI dipastikan menjadi catatan bagi lembaga-lembaga yang terkena indeks persepsi buruk.
Pun sekali beberapa bulan lembaga survei politik juga merilis hasil “approval rating” Jokowi, dengan hasil yang tidak selalu sempurna, tidak melulu di atas angka yang diharapkan oleh Jokowi dan pendukungnya.
Namun di saat Jokowi berkuasa, hasil tersebut akan dijadikan bahan evaluasi, mengapa approval-nya bisa turun, pada bagian mana yang memburuk, dan seterusnya. Lagi-lagi akhirnya semuanya berlalu dan “fine-fine” saja.
Lantas karena topik yang disurvei oleh sebuah lembaga ternyata sangat tidak sesuai dengan harapan pendukung Jokowi, tidak berarti harus ditolak sebagai hasil survei.
Tentu dipersilahkan mempersoalkan hasil surveinya, persis seperti lembaga-lembaga negara yang masuk daftar Transparansi Internasional tadi, misalnya, yang boleh-boleh saja berkilah untuk menolak atau mendelegitimasi hasil survei TI. Tak ada masalah dengan sikap yang demikian.
Namun lebih dari itu, karena isunya hanya sebatas hasil survei yang sangat bergantung kepada persepsi dari para pihak yang disurvei, maka kali ini, baik Jokowi maupun para pendukungnya di satu sisi dan para buzzer beserta peternak-nya di sisi lain, harus mulai belajar bahwa ada kalanya persepsi publik tidak bisa di-setir, tak bisa dijejali narasi-narasi yang sesuai dengan keinginan, alias harusnya mulai menapakkan kaki di bumi secara nyata dan menerimanya sebagai hasil survei.
Toh, semua orang juga mengetahui bahwa daftar tersebut adalah hasil survei, bukan gugatan hukum.
Setidaknya secara hukum Jokowi tetap tak ada masalah alias baik-baik saja. Begitu juga dengan gerbong-gerbong yang pernah mencari makan di istananya.
Perkara reputasi yang terganggu, nampaknya sudah bukan waktunya lagi Jokowi memikirkan hal itu. Menikmati pensiun yang nyaman sembari menimang-nimang cucu akan jauh lebih baik bagi Jokowi saat ini.
Bagi pendukungnya pun demikian. Terimalah hasil survei OCCRP sebagai sebuah hasil survei. Sebatas itupun tak adalah masalah. Ya, sebatas hasil survei maksudnya. It’s ok.
Semua orang juga memahami bahwa untuk mengakui itu sebagai fakta sosial politik tidak akan pernah bisa dilakukan, baik oleh Jokowi maupun oleh pendukung dan para buzzer-nya, meskipun tak sedikit orang juga mengakuinya di dalam hati bahwa memang demikanlah nyatanya sepuluh tahun era pemerintahan Jokowi.
Karena pengakuan semacam ini hanya akan meruntuhkan istana yang telah dibangun selama kurun waktu sepuluh tahun Jokowi berkuasa.
Perkara bagaimana metodologinya, silahkan diperdebatkan dengan OCCRP. Jika perlu buatlah semacam survei tandingan yang akan menempatkan Jokowi sebagai pemimpin terbersih di dunia. Toh tak ada yang melarang, tentunya jika memang masih bisa mendapatkan sponsor untuk itu.
Jika tidak, lagi-lagi ya terima saja itu sebagai hasil survei. Sekali lagi, sebagai hasil survei saja. Tak perlu malu-malu mengecilkan ruangnya sebagai hasil survei semata, karena daftar tersebut memang lahir dari survei.
Toh saya yakin, sebagaimana banyak pihak lain juga meyakini, isu ini akan hilang dalam waktu yang sangat pendek.
Tinggal menunggu isu seksi lainnya muncul, maka isu ini akan “kebanting” seketika. Seperti kata Gus Dur, “gitu saja kok repot”. Salam optimis menjalani Tahun Baru 2025.



![[POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota](https://asset.kompas.com/crops/SCa7e6NsX0q7xzJOzm6czodJazQ=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/11/20/673dbf7febba3.jpg)