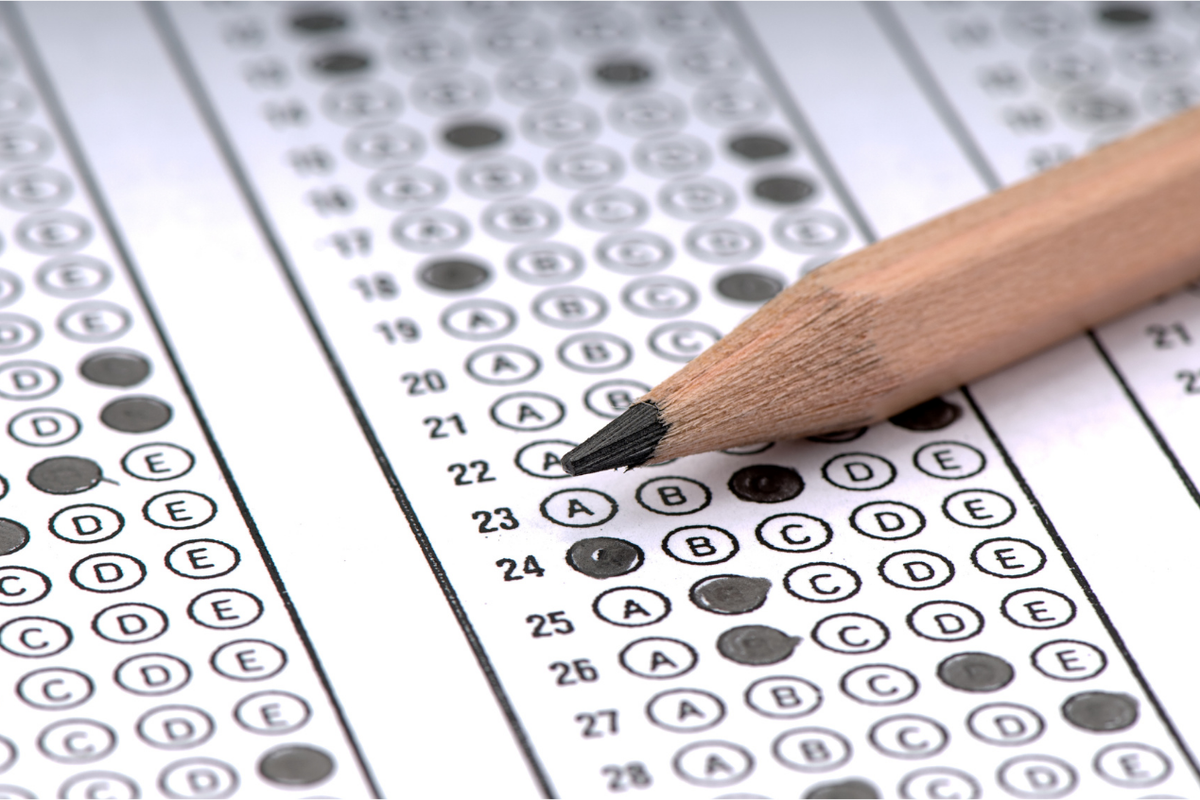Pertaruhan Format Baru Ujian Nasional

Wacana kembalinya Ujian Nasional (UN) ke sistem pendidikan Indonesia mengundang diskusi kritis di tengah masyarakat. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti bahwa pelaksanaan UN baru akan dilakukan setelah 2025 dengan format baru, memberi harapan sekaligus skeptisisme. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini adalah langkah maju atau justru pengulangan kesalahan masa lalu dalam sistem pendidikan kita yang sering tidak konsisten.
UN dalam Sejarah Instrumen Evaluasi atau Beban Sistem?
Selama beberapa dekade, UN telah menjadi simbol evaluasi pendidikan Indonesia. Namun, ia juga menjadi alat yang sering kali dipertanyakan efektivitasnya. Fungsi utamanya untuk mengukur kualitas pendidikan di tingkat nasional seringkali tergeser oleh perannya sebagai penentu kelulusan siswa, alat seleksi penerimaan peserta didik baru, dan bahkan indikator prestise sekolah.
Masalahnya, UN cenderung menjadi momok bagi siswa dan guru. Ketika hasil UN menjadi syarat mutlak kelulusan, tekanan yang muncul tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh sekolah yang berlomba-lomba menjaga reputasi. Hal ini mendorong berbagai bentuk penyimpangan, seperti kecurangan sistematis hingga pengajaran yang hanya berfokus pada materi UN (teaching to the test), yang pada akhirnya mereduksi esensi pendidikan itu sendiri.
Lebih dari itu, UN seringkali menciptakan ketidakadilan struktural. Siswa dari daerah terpencil dengan fasilitas minim menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berasal dari sekolah di daerah perkotaan dengan sumber daya melimpah. Ketimpangan ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru memperdalam jurang kualitas pendidikan.
UN dan Kritik Esensial Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara
Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengejar kepandaian akademis, tetapi juga membangun jiwa dan karakter peserta didik. Prinsip ini terangkum dalam konsep Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) serta filosofi Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Menurutnya, pendidikan harus menjadi proses yang membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi manusia secara utuh.
Dalam konteks ini, format lama UN yang cenderung mengukur keberhasilan pendidikan hanya melalui kemampuan akademis bertentangan dengan visi pendidikan Ki Hadjar. UN sering menciptakan lingkungan kompetitif yang tidak sehat, di mana siswa dipaksa untuk menghafal demi nilai, bukan untuk memahami esensi dari apa yang mereka pelajari. Lebih buruk lagi, UN telah memperkuat budaya pendidikan yang seragam, mengabaikan keragaman kebutuhan dan potensi individu siswa di berbagai daerah.
Sebaliknya, Ki Hadjar menginginkan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan siswa dan relevan dengan kehidupan mereka. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang tidak bisa diukur hanya dengan satu jenis evaluasi, apalagi evaluasi yang bersifat nasional dan terstandarisasi.
Format Baru Solusi atau Sekadar Rebranding?
Janji pemerintah untuk menghadirkan format baru UN tentu layak diapresiasi. Prof. Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa hanya sekolah terakreditasi yang akan menjadi penyelenggara UN. Selain itu, format ini dirancang untuk menjadi lebih komprehensif dan tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan.
Namun, pernyataan tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Seperti apa konkret perubahan yang dijanjikan? Apakah format baru ini hanya perubahan kosmetik, atau benar-benar akan merevolusi cara kita mengevaluasi pendidikan? Kekhawatiran ini muncul mengingat sejarah pendidikan Indonesia yang sering lebih fokus pada pencitraan kebijakan daripada dampaknya di lapangan.
Sebagai contoh, janji untuk mengubah UN menjadi alat diagnosis kualitas pendidikan nasional adalah langkah yang baik, tetapi hal ini membutuhkan infrastruktur data yang andal, tim analisis yang kompeten, dan pelaksanaan yang bebas dari intervensi politis. Jika tidak, hasil UN hanya akan menjadi angka-angka statistik yang tidak bermakna dalam perbaikan sistem pendidikan.
Gonta-Ganti Kebijakan Cerminan Inkonsistensi atau Dinamika?
Sebagai tokoh pendidikan yang konsisten dengan prinsipnya, Ki Hadjar Dewantara mengkritik sistem pendidikan kolonial Belanda yang seragam dan elitis. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan konsisten, dengan tujuan jangka panjang yang jelas. Dalam pandangan ini, fenomena gonta-ganti kebijakan pendidikan di Indonesia mencerminkan lemahnya perencanaan strategis dalam sistem pendidikan nasional.
Perubahan kebijakan yang sering terjadi, seperti penghapusan UN beberapa tahun lalu dan wacana pengembaliannya sekarang, menunjukkan kurangnya arah yang jelas dalam sistem pendidikan kita. Kebijakan seperti ini sering kali diambil secara reaksioner untuk merespons isu-isu sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi siswa, guru, dan masyarakat.
Ki Hadjar menekankan bahwa pendidikan harus dirancang untuk membangun fondasi bangsa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif atau politis. Dengan kata lain, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang stabil, berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, dan mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
Kembalinya UN, Apa yang Dipertaruhkan?
Kembalinya UN dengan format baru membawa peluang besar, tetapi juga risiko yang tidak bisa diabaikan. Peluang terbesar terletak pada kemampuan pemerintah untuk menjadikan UN sebagai alat evaluasi berbasis data yang dapat memetakan kualitas pendidikan secara nasional. Dengan demikian, hasil UN bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif.
Namun, risikonya jauh lebih kompleks. Jika implementasi format baru tidak didukung oleh persiapan matang, kebijakan ini bisa menjadi bumerang. Misalnya, fokus pada sekolah terakreditasi sebagai penyelenggara UN dapat menciptakan eksklusivitas baru yang menambah beban bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Selain itu, tanpa transparansi dalam desain dan pelaksanaan, format baru ini bisa gagal mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Selain itu, ada ancaman lain yang lebih subtil bagaimana kebijakan ini mempengaruhi filosofi pendidikan kita? Pendidikan seharusnya menjadi proses pembelajaran yang holistik, bukan sekadar pencapaian angka-angka di atas kertas. Jika UN, meski dalam format baru, tetap berfokus pada evaluasi kognitif, maka kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama mengabaikan potensi siswa yang tidak dapat diukur dengan tes standar.
Reformasi atau Ilusi Perubahan?
Kembalinya Ujian Nasional adalah momen refleksi bagi sistem pendidikan Indonesia. Jika dilakukan dengan benar, kebijakan ini bisa menjadi katalisator untuk reformasi besar-besaran, menjadikan evaluasi pendidikan sebagai alat diagnostik yang mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Namun, jika hanya menjadi rebranding dari sistem lama, maka kebijakan ini berisiko memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendidikan nasional.
Di tengah dinamika ini, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada prinsip pendidikan yang inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Konsistensi kebijakan, persiapan matang, dan transparansi harus menjadi fondasi dalam pelaksanaan format baru ini. Pada akhirnya, pendidikan bukanlah soal pencapaian angka, tetapi tentang mencetak generasi yang mampu berpikir kritis, berkarakter kuat, dan siap berkontribusi pada masyarakat. Semoga kembalinya UN bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar menjadi langkah maju menuju pendidikan berkualitas di Indonesia.
Karunia Kalifah Wijaya pemerhati pendidikan