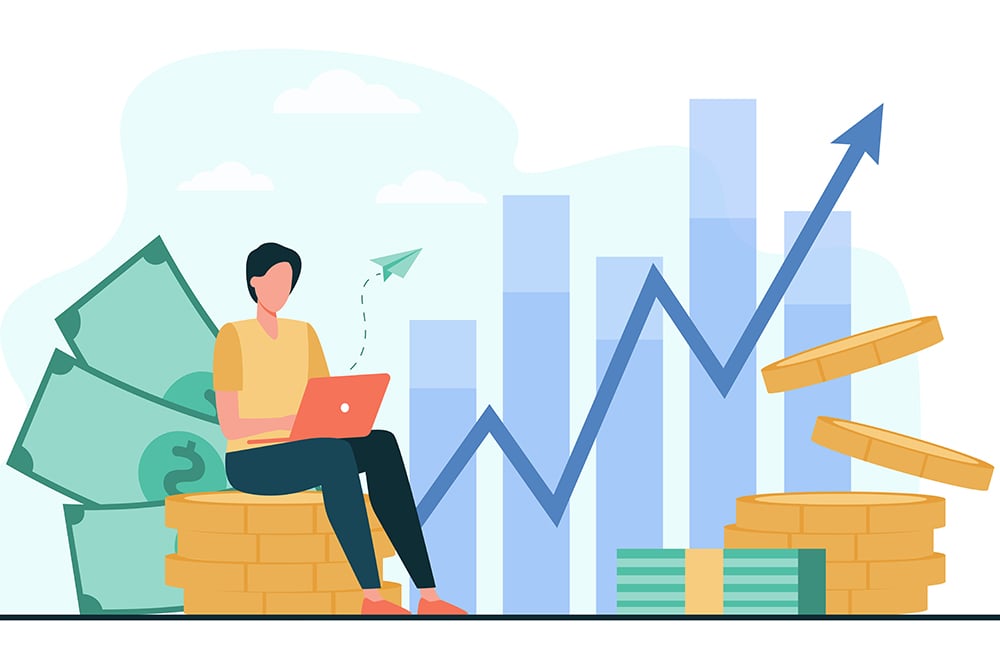Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek industri manufaktur nasional pada 2025 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, mulai dari gempuran produk impor asal China, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hingga upah minimum 6,5%.
Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
“Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024).
Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.
Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut.
Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini.
“Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.
Telisa juga menyebut penyesuaian PPN semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif.
"Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga," ujarnya.
Telisa juga menyoroti bagaimana penambahan biaya akibat kenaikan tarif PPN dan upah minimum bakal mempengaruhi harga produk yang pada akhirnya harus ditanggung konsumen. Dia memahami bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan tax ratio sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara.
Namun, ironisnya, kondisi ekonomi saat ini dengan daya beli masyarakat yang sedang menurun justru memperlihatkan bahwa kebijakan ini mungkin tidak tepat secara waktu.
"PPN dinaikan untuk meningkatkan tax ratio. Kondisi masyarakat kurang memungkinkan ditengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Adanya stimulus sebagai mitigasi," terangnya.
Dia menilai agar kebijakan PPN sebaiknya difokuskan pada barang mewah untuk mengurangi dampak regresif dari PPN semakin meluas dan cenderung permanen.
Ekonom Senior, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa seharusnya alih-alih menyalahkan China, seharusnya industri lokal dibenahi terutama dalam hal absorptive capacity yaitu kemampuan suatu industri untuk dapat menyerap investasi secara efektif.
“Absorptive capacity itu dibangun berdasar tiga pilar, yaitu infrastruktur, SDM, dan institusi. Ketiga hal tersebut berpengaruh pada daya serap investasi. Misalnya SDM, gimana investasi bisa terjadi jika ternyata talenta yang diperlukan di industri tersebut tidak ada?” kata Fithra.
Dalam hal ini, dia menegaskan pentingnya tinjauan ulang kebijakan PPN untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri nasional.
Menurut Fithra, industri setidaknya harus memiliki pertumbuhan ekonomi 27% secara kontribusi dengan 3 pilar yaitu SDM, infrastruktur, institusi agar tidak kehilangan momentum industrialisasi.