Untuk Apa Reposisi Polri ke Barak Militer dan Kementerian?
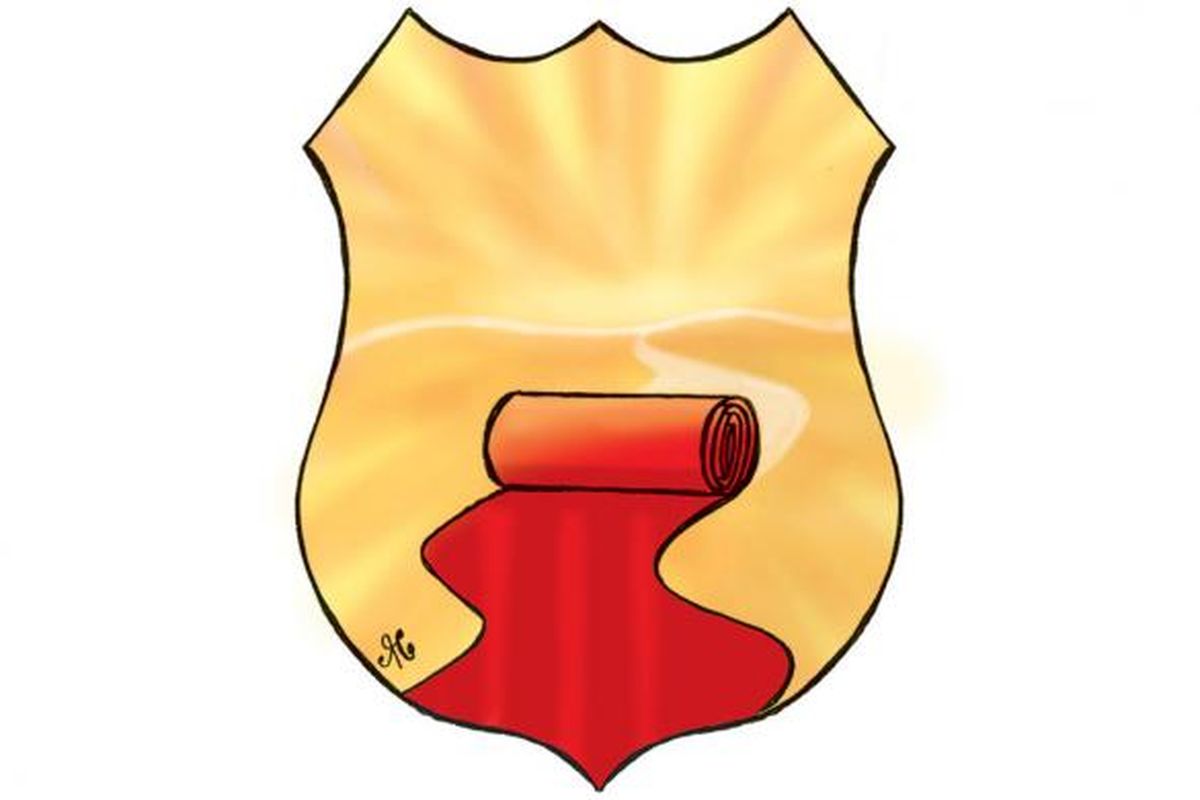
SECARA mengejutkan, politisi PDIP menyerukan Reformasi total terhadap institusi Kepolisian. Banyak orang yang bertanya-tanya, ada apa di balik kritikan tajam para politisi PDIP terhadap Polri?
Rupanya PDIP merasa kecewa dengan sikap polisi yang menurut mereka telah menjadi alat politik. Polri sudah dianggap menjadi institusi super power dan multi fungsi, sehingga tidak mampu lagi dikendalikan.
PDIP melemparkan wacana mengembalikan Kepolisian ke Militer atau di bawah kementerian. Polisi dituduh menjadi alat politik atau semacam partai yang bekerja untuk kepentingan politik tertentu.
Ketegangan memuncak setelah muncul istilah Parcok (Partai Coklat), istilah yang memojokkan polisi, dianggap bekerja layaknya partai politik dalam kontestasi Pemilu.
Tuduhan itu cukup serius karena menyangkut profesionalisme dan akuntabilitas lembaga Kepolisian.
Persoalanya kemudian, kenapa isu "Partai Coklat" ini muncul setelah suksesi politik? Kenapa dari awal tidak diantisipasi sebagai bahaya, sehingga PDIP sebagai partai terbesar bisa lebih awal menghentikan pergerakan polisi?
Tuduhan itu baru muncul setelah PDIP menghadapi kekalahan di sejumlah daerah pada Pilkada 2024. Kekalahan PDIP di "kandang Banteng" Jawa Tengah dan di berbagai daerah yang menjadi basis politik PDIP, menjadi motif utama yang menyebabkan partai itu menyoal institusi Kepolisian.
Kekalahan PDIP di berbagai daerah bukan fenomena luar biasa. Salah satu faktor kekalahan karena sikap politik PDIP selama 10 tahun berkuasa.
Kekalahan yang sama juga dialami partai-partai lain. Psikologi politik masyarakat, apalagi daerah Jawa dan sekitarnya, sangat dipengaruhi dinamika politik nasional.
Perubahan rezim di tingkat nasional dan lokal, mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari fenomena politik biasa yang tidak ada kaitannya dengan institusi tertentu.
Sudah lumrah terjadi, apabila kekuasaan berganti, maka arah politik juga akan berubah.
Dulu, PDIP pernah menikmati sebagai partai pemenang dan partai berkuasa, nuansa politiknya masih sama, yaitu psikologi politik selalu mengikuti alur kekuasaan.
Banyak partai yang mengalami kekalahan serupa karena menjadi oposisi terhadap penguasa. Ini bukan karena adanya intervensi politik, tetapi memang kehendak masyarakat yang selalu ingin agar pemerintahan lokal memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan nasional.
Menurut pendapat ini, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah daerah akan lebih menjamin dapat dilaksanakan apabila gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari partai penguasa atau setidaknya didukung oleh penguasa.
Dari perspektif politik integral seperti ini, menurut hemat saya, agak berlebihan memberikan predikat kepada Polri sebagai institusi yang mengatur Pilkada.
Namun, keberadaan polisi dalam struktur pengamanan dan penegakan hukum Pemilu sejauh ini tidak dapat dipungkiri bahwa polisi ikut bekerja dalam Pemilu. Karena posisi tersebut, tentu memberikan stigma bahwa polisi juga dapat mengatur urusan pemilu.
Sebab, polisi ada di mana-mana dan ditempatkan di mana-mana. Ada polisi yang setiap hari berkantor di KPU. Di Sentra Gakkumdu, ada polisi sebagai penyidik dan penegak hukum Pemilu bersama Bawaslu.
Dalam konteks ini memang polisi dapat dikaitkan dengan politik elektoral, karena UU memberikan kewenangan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam Pemilu.
Namun, menyebutkan ada intervensi Polri terhadap hasil Pemilu, masih perlu dibuktikan secara komprehensif.
Terlepas dari semua isu yang berkembang belakangan ini, secara institusional, Polri memang perlu dievaluasi. Ini bukan sekadar evaluasi kelembagaan, melainkan evaluasi sistemik, sehingga Polri dapat berbenah.
Institusi Kepolisian di seluruh dunia pada umumnya dianggap korup. Seperti di Polri, ada sejumlah oknum yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi.
Hal ini tidak mengherankan. Mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki polisi dan terbatasnya pengawasan yang mereka hadapi, para polisi menyerah pada godaan dan terlibat dalam praktik korupsi.
Seperti kata Robert Armstrong (2012), penyimpangan polisi tidak mengenal batas. Polisi seringkali menjadi penyokong status quo dengan melindungi rezim politik.
Dalam banyak kasus, polisi menjadi pelengkap bagi kejahatan elite penguasa, seperti otoritarianisme dan pelanggaran HAM.
Kenapa polisi menjadi sangat jelek dalam berperilaku? Perilaku individu ini secara objektif tidak dapat dituduhkan kepada lembaga. Namun, apabila perilaku individu sudah menyasar di semua tempat, maka sudah sepantasnya menyoal institusinya.
Kasus polisi menembak polisi, kasus polisi yang terlibat jual beli Narkoba, kasus polisi menggunakan kekerasan pada masyarakat dan penggunaan senjata di luar hukum sudah terjadi berkali-kali. Ini menjadi problem serius kalau tidak dilakukan pembenahan institusional.
Penyebab dari persoalan itu setidaknya berakar pada beberapa hal, yaitu
Pertama, polisi sebagai penegak hukum adalah institusi yang paling rentan menyalahgunakan wewenang.
Faktanya, di banyak negara berkembang, perilaku penegakan hukum oleh polisi telah merosot menjadi tindakan polisi predator yang melanggar hukum. Di sini didefinisikan sebagai kegiatan memperkaya diri sendiri dan mempertahankan diri, bukan untuk melindungi masyarakat.
Polisi menegakkan hukum dan ketertiban sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Polisi dapat memeras pengemudi taksi, pedagang pasar, dan pemilik toko.
Ketika korban melapor tindak kejahatan, polisi menolak menyelidiki jika korban tidak membayar sejumlah uang.
Sementara itu, penjahat berdompet tebal menyuap polisi untuk menghindari penangkapan atau penuntutan, untuk memengaruhi hasil penyelidikan kriminal, atau bahkan untuk membalikkan penyelidikan terhadap korban.
Perwira polisi senior mengambil bagian dari uang yang diperas oleh perwira yunior. Pola korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasinya juga terjadi di sebagian besar negara berkembang. Persoalan ini sudah mengakar dalam Kepolisian.
Persoalan kedua adalah masalah sumber daya dan rekruitmen polisi. Sumber daya meliputi gaji rendah dan fasilitas yang tidak memadai.
Sementara sistem rekruitmen sumber daya masih menggunakan kedekatan dan uang. Tidak mengherankan, ada sejumlah polisi yang tidak memiliki integritas.
Ketiga, sistem akuntabilitas sebagai pengontrol perilaku Kepolisian tidak berjalan. Penyalahgunaan wewenang pada umumnya mencerminkan kurangnya akuntabilitas kepemimpinan dan komando.
Karena itu perlu pengawasan eksternal yang aktif dan maksimal di samping pengawasan internal. Tanpa pengawasan, maka akuntabilitas kinerja polisi akan semakin hancur.
Keempat, persoalan tradisi budaya masyarakat. Adat istiadat masyarakat sangat menentukan profesionalitas kelembagaan.
Faktor budaya sebagai penyebab tumpulnya penegakan hukum yang profesional dan sikap mementingkan diri sendiri.
Penghambat ini telah menyeret polisi pada budaya birokrasi yang feodal dan kaku, sehingga menghasilkan kinerja yang tidak memiliki standar etika. Budaya organisasi yang tidak memiliki etos kerja yang baik akan menjadi pemicu lahirnya birokrasi bobrok.
Meskipun faktanya polisi sedang menghadapi terpaan, apalagi muncul keinginan untuk menarik kembali Polri di bawah TNI atau kementerian, tentu akan menimbulkan perdebatan dan polemik.
Polemik ini harus diarahkan pada perbaikan institusi secara sistemik, bukan reposisi kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Sepanjang rute sejarah, kelembagaan Polri telah mengalami reposisi berkali-kali. Pada awal kemerdekaan, kedudukan Kepolisian ditempatkan di bawah kementerian. Tahun 1945, polisi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Setahun setelah merdeka pada 1 Juni 1946, Kepolisian ditempatkan di bawah perdana menteri. Pada 1948, karena Indonesia menganut sistem presidensial, posisi polisi kemudian di tempatkan di bawah presiden dan wakil presiden.
Selama Republik Indonesia Serikat Kedudukan Polisi diatur dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950. Keppres itu menyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung. Sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.
Dari tahun 1950-1959, setelah RIS dibubarkan, polisi ditempatkan di bawah perdana menteri. Selama masa itu kedudukan polisi berada di bawah kementerian.
Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit itu juga memengaruhi kedudukan Kepolisian dalam struktur ketatanegaraan.
Kedudukan Kepolsian yang tadinya di bawah perdana menteri kemudian diberikan kedudukan setingkat kementerian negara.
Setelah Soekarno mulai debut demokrasi terpimpinnya, membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang akhirnya menempatkan Kepolisian di bawah ABRI hingga Reformasi 1998.
Setelah dwi-fungsi ABRI dicabut, Kepolisian kemudian dipisah dari TNI dan ditempatkan langsung di bawah presiden.
Dari sejarah tersebut terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu presidensil dan parlementer. Dalam sistem parlementer, kedudukan polisi berada di bawah menteri. Sedangkan dalam sistem presidensial, kedudukan polisi berada langsung di bawah presiden.
Karena itu, reposisi Kepolisian agar ditempatkan di bawah kementerian negara dalam sistem presidensial akan memperumit kedudukan kelembagaan Polri. Setelah Reformasi, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, bukan parlementer.
Karena itu, menurut hemat saya, tidak ada alasan kuat untuk mengembalikan kedudukan Polri di bawah kementerian sebagaimana yang pernah terjadi pada masa demokrasi parlementer masa lalu.
Menyoal reposisi institusional tidak akan mengakhiri masalah yang terjadi dalam internal Polri. Langkah yang paling mungkin adalah memperbaiki sistem kelembagaan melalui reformasi sistem.
Ada dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan sistemik. Pertama, faktor eksternal seperti perubahan perilaku masyarakat.
Kedua, faktor internal organisasi yang mencakup dua hal pokok, yaitu 1) perubahan struktural meliputi perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem serta; 2) perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi.
Perubahan eksternal akan diawali dengan perbaikan sistem hukum dan pengawasan terhadap institusi. Menjadikan institusi Kepolisian semakin terbuka dan dapat dikritik oleh masyarakat luas tanpa takut akan ancaman pidana dan kekerasan.
Perubahan eksternal juga bisa terjadi dengan perubahan UU mengenai kewenangan polisi. Misalnya, dalam KUHAP baru, kewenangan penyidikan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kewenangan polisi, melainkan diberikan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.
Ketentuan tersebut memungkinkan polisi tidak lagi dapat bermain dengan kasus-kasus yang dilidiknya.
Sementara perubahan kultural dalam institusi Kepolisian dapat dilakukan mulai rekruitmen polisi yang transparan tanpa suap. Pengangkatan perwira menengah dan perwira tinggi harus dilakukan dengan proses terbuka dan uji publik.
Selain itu, perbaikan institusional harus dilakukan dengan sedapat mungkin membatasi kewenangan polisi dalam berbagai lembaga, termasuk keterlibatan polisi dalam persoalan Pemilu dan lainnya.
Pembatasan ini penting agar terhindar konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Dengan pembatasan demikian, polisi akan memiliki ruang gerak terbatas.
Terlepas dari semua polemik tersebut, Polri harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga menjadi institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, menjaga ketertiban dan keamanan serta melakukan penegakan hukum yang adil.







